SM Ardan
(1932-2006)
Sastrawan dan Tokoh Film Nasional Penyelamat Teater Rakyat Betawi
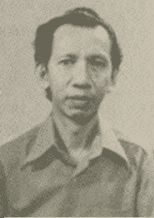
Kesenian Betawi banyak berhutang budi kepada SM Ardan. Pertama, karya sastranya membantu penyelidikan mengenai Betawi-Jakarta. Sebab mendokumentasikan bermacam unsur tradisi-budaya Betawi. Kedua, ia meneliti aneka kesenian Betawi, terutama lenong, agar hidup kembali dengan mengajak senimannya tetap menjaga tradisi sambil mebawa inovasi baru ke dalamnya melalui kerja-kerja menggubah lakon dan penyutradaraan.
Ardan lahir di Medan 2 Februari 1932. Namun, ia tulen beribu bapak Betawi, yaitu Muhamad Zein dan Nursyah. Ayahnya tukang potret yang merantau ke Medan. Mereka kembali ke Jakarta saat Ardan berumur enam tahun dan tinggal di kampung Kwitang dekat pusat urban Senen. Ia tumbuh di antara anak-anak Betawi-Jakarta dan mengalami suka-duka mereka sebagai orang kecil. Ardan tidak diragukan lagi adalah “orang dalam” Betawi-Jakarta.
Meskipun SMA di Taman Siswa tidak ditamatkan Ardan, tetapi ia dianggap teman sekolahnya yang sudah terkenal sebagai penulis—Soekanto SA, Misbach Jusa Biran, Sobron Aidit—sosok yang pemikirannya paling depan. Ardan ditahbiskan sebagai pemimpin kelompok “Seniman Senen cabang Taman Siswa”.
Ardan memulai karir tulis menulisnya sejak masa sekolah dengan menjadi redaktur majalah sekolah Taman Siswa di Jakarta, yaitu Suluh (1953–1954). Dari sini ia mulai memperkenalkan diri di media kebudayaan nasional sebagai penulis sajak. Buku pertamanya yang erbit 1955 pun kumpulan sajak bertiga dengan kawannya di Taman Siswa—Ajip Rosidi dan Sobron Aidit—berjudul Ketemu di Jalan.
Selain menulis sajak, Ardan mengulas film, teater, sastra di berbagai media tersohor, antara lain Mimbar Indonesia, Zenith, Kisah, Indonesia, Siasat dan Pujangga Baru. Bersamaan ia menjadi redaktur majalah Pena. Lantas mengomandani berderet media, seperti majalah Arus (1954), majalah Genta (1955-1956), Trio (1958), Abad Muslimin (1966). Termasuk Berita Minggu Suluh Indonesia (1959–1966).
Pada pertengahan 1950-an, tema dunia rakyat Betawi-Jakarta dalam sastra Indonesia bukanlah hal baru. Aman D. Madjoindo telah mulai dengan menulis Si Dul Anak Betawi. Lantas M. Balfas dengan Si Gomar. Namun, keduanya tidak menulis dalam bahasa Betawi. Madjoindo ejaannya saja yang Betawi, tetapi gaya dan jiwanya Indonesia-Minang. Balfas lebih murni dari Madjoindo. Ia menggunakan omong Betawi Ora’ tetapi kebelanda-belandaan. Di sinilah kelebihan Ardan karena ia memakai dialek Betawi yang nyata benar kewajarannya.
Cerpen-cerpen Ardan populer karena menampilkan warna lokal dan kepribadian budaya yang sedang ramai dibicarakan pada 1950an. Beberapa cerpen itu kemudian dibukukan dalam kumpulan Terang Bulan Terang di Kali yang diterbitkan Gunung Agung pada 1956. Meskipun karyanya menggunakan bahasa Betawi, tetapi dianggap memperkaya kesusastraan Indonesia.
Kumpulan cerpen Ardan menunjukkan ia tak pernah terasing dari tradisi dan rakyat kecil Betawi-Jakarta. Betapa ia sedih atas bahaya-bahaya yang mengancam mereka. Kemiskinan, kebodohan, ketakutan, dan penyakit yang membekap mereka bukanlah takdir, melainkan suatu sistem jahat yang sengaja dibangun dari atas. Mereka bukan pemalas, tetapi pekerja ulet dan memegang prinsip kebersamaan, keberagaman serta etik moral lainnya.
Pada 1950-an, Ardan juga menulis naskah film, seperti Terang Bulan Terang di Kali (1956), Di Balik Dinding (1956). Sedangkan karirnya sebagai orang teater mulai menonjol pada 1960-an. Saat itu ia menjadi ketua Seksi Teater Kuncup Harapan. Saking terkenal di antara generasi baru siswa sekolah yang berminat sastra, kelompok sandiwara ini kerap membuat pertunjukan di Jakarta dan beberapa kota lainnya di Indonesia serta tampil mengisi acara TVRI yang baru berdiri.
Pada 1965, Ardan menulis ulang cerita Nyai Dasima. Ia membongkar praktik busuk kolonialisme yang berjalan via bacaan rakyat. Di cerita Dasima dari akhir abad ke-19 karya G Francis semua orang pribumi digambarkan buruk, tetapi sebaliknya orang kulit putih. Hanya mereka yang baik. Namun, dari semua nyai yang terburuk. Padahal bagi Ardan kata nyai itu adalah simbol kemuliaan. Demikianlah ia membalik kisah Francis menjadi cerita nyai yang sejati, perempuan yang punya sikap dan harga diri serta keberanian pulang ke tengah bangsanya seraya menolak semua keisitimewaan menjadi “bini piara” tuan Eropa.
Ketika di Jakarta berdiri Taman Ismail Marzuki (TIM) dan Gubenur Ali Sadikin punya perhatian besar terhadap kebetawian, Ardan bareng kawan-kawannya sejak 1969 meneliti aneka kesenian Betawi, terutama lenong. Menurut Ardan “lenong dan seni Betawi lainnya berada di pinggir jurang kematian pada 1960an. Pesatnya perkembangan Jakarta sebagai ibukota sejak 1950 telah memojokkan Lenong sehingga nyaris punah...” Situasi yang dilihat Ardan itu sesungguhnya akibat dari masa penjajahan Jepang dan perang kemerdekaan ditambah larangan pemerintah kota pertunjukan tradisi ngamen yang membawa akibat kesenian Betawi tidak bisa berkembang.
Berkat jasanya ini, lenong bangkit dan menjadi tontonan populer. Disusul Ondel-Ondel, Tanjidor dll. Lenong muncul di televisi dan menyebar melalui panggung hiburan lainnya. Pemain Lenong pun masuk layar perak. Teater modern pun mengadopsi Lenong mulai dari Arifin C. Noer sampai Nano Riantiarno. Ardan pun menggarap naskah lenong, seperti Buronan Teluk Naga, Mandor Bego, pendekar Bodo, Si Gohang, Ronggeng Krawang, Nyai Saiah, Abunawas, dan tentu saja Nyai Dasima yang sudah terkenal sejak 1960-an.
Hampir bersamaan ia mengelola media perfilman, seperti Violeta (1972–1977) dan Citra Film (1981-1982). Namun, terpenting saat itu ia membantu sahabatnya, Misbach Jusa Biran, mendirikan Sinematek, pusat dokumentasi dan riset film. Ia juga aktif menulis skenario film bertema Betawi-Jakarta, seperti Si Pitung (1970), Si Gondrong (1971), Brandal-Brandal Metropolitan (1971), Pendekar Sumur Tujuh (1971), dan Pembalasan Si Pitung (1977).
Setelah menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) selama dua periode, 1982–1990, Ardan menghabiskan waktunya bekerja di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail (PPHUI) dan menulis buku sejarah Film Indonesia 1926–1950 bersama Taufik Abdullah serta Misbach Jusa Biran. Ia meninggal setelah kecelakaan tertabrak sepeda motor tak jauh dari rumahnya di Rawabelong, Jakarta Barat, dan kemudian dimakamkan di pekuburan Karet.